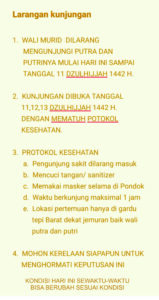Oleh: @syahronieimam
Sudah seminggu lampu kamar tak dinyalakan. Bukan karena rusak, tapi karena Elara tak sanggup menatap bayangannya sendiri—yang selalu menangis lebih dulu darinya, seolah tahu luka sebelum ia sempat bicara. Ia lebih memilih gelap; tempat di mana tangis bisa sembunyi dan luka pura-pura tak ada.
Enam belas tahun. Bagi anak lain, itu usia tawa dan pesta kecil. Tapi bagi Elara, angka itu terasa retak—seperti jendela tua yang menghadap jurang. Rumah tempatnya tinggal berdiri ringkih di ujung gang, berlantai kayu yang mengeluh setiap kali disentuh langkah. Seakan rumah itu pun lelah menanggung hidup yang terus dibiarkan patah.
Ia tinggal bersama nenek yang perlahan lupa akan cucunya. Kadang memanggilnya dengan nama ibunya, kadang hanya diam menatap. Dan Elara pun diam. Ia tak tahu lagi kepada siapa harus bercerita. Ia tumbuh bersama waktu yang berjalan, meski ia sendiri tak tahu untuk apa.
Setiap pagi, Elara menyeduh teh yang dingin sebelum sempat diseruput. Ia duduk di meja retak itu, menatap kursi kosong di depannya. Menunggu suara yang dulu berkata: “Minumlah perlahan, agar hangatnya sempat bicara dengan tubuhmu.”
Tapi tak ada suara yang kembali. Hanya detak jam tua yang berdetak seperti langkah Tuhan yang berjalan pelan, takut mengganggu kesedihan yang sedang tumbuh.
Kadang malam terasa lebih nyata. Elara tak berdoa dengan tangan terangkat, melainkan dengan mata yang terbuka lebar—menatap sudut kamar yang paling gelap, tempat ia percaya Tuhan duduk, diam, tak berkata apa-apa. Tapi mendengar.
Ia tak memohon surga. Ia tak memohon bahagia. Ia hanya ingin ada ruang kecil di dunia ini, tempat ia bisa menangis tanpa dianggap lemah. Neneknya mulai sering bicara sendiri. Kadang memanggil Elara dengan nama ibunya. Kadang menangis sambil menyebut ayat-ayat yang tak selesai.
“Elara ya? Sudah makan, Nak?” “Iya, Nek. Sudah.” Kebohongan kecil yang Elara pelajari untuk menjaga dunia mereka tetap berdiri, seperti kursi tua yang tidak boleh diduduki di satu sisi karena bisa patah.
Malam itu, ketika nenek tertidur—napasnya pendek dan tersendat, seperti daun yang tertahan angin—Elara duduk di lantai kamar. Ia menggenggam potongan baju ibunya yang masih menyisakan wangi kenangan: samar, tapi tak pernah benar-benar hilang.
“Tuhan, aku tidak minta diselamatkan. Hanya… kalau besok aku tidak ada, tolong jangan bilang aku menyerah. Katakan saja aku terlalu diam hingga tak terdengar.”
Sebelum dunia diam dan patah perlahan, Elara hidup di rumah mungil bersama ibu, ayah, dan nenek. Tak luas, tak mewah—tapi cukup. Di sanalah cahaya tawa kecil menggantung di langit-langit, memeluk malam sebelum mata benar-benar terpejam. Mereka tidak kaya, tapi hangat. Ibunya pandai bercerita. Setiap malam, suara ibunya mendongeng tentang bintang-bintang yang jatuh bukan karena kalah, tapi karena ingin lebih dekat dengan bumi.
Sesekali, mereka membuat teh manis bersama di dapur kecil yang hangat. Elara paling senang menunggu uapnya naik, perlahan membentuk kabut di kaca jendela. Saat itu, ibunya akan mencium keningnya lalu berbisik:
“Kalau kabutnya menghilang, itu tandanya malaikat baru saja lewat.” Tapi malaikat tak selalu datang.
Dan suatu pagi yang ganjil, ayah memutuskan merantau ke Malaysia—katanya demi memperbaiki nasib. Elara kecil hanya tahu satu hal: lutut ayah adalah tempat paling aman di dunia. Maka di stasiun keberangkatan, ia menangis sambil memeluknya erat, seolah peluk bisa menahan jarak.
“Ayah nggak lama, kok. Pasti cepat pulang. Bawa boneka buat Lara,” katanya sambil tersenyum, lalu hilang ditelan kereta dan jarak. Awalnya, suara Ayah masih pulang. Lewat video singkat, janji-janji, dan kiriman uang.
Tapi waktu memisahkan lebih dari sekadar jarak. Bulan-bulan berlalu, dan suara itu lenyap. Tak ada lagi kabar. Nama Ayah pun perlahan hilang dari percakapan.
Hingga suatu sore, kabar datang dari seorang teman: Ayah kini tinggal bersama perempuan lain. Ia memilih pergi, meninggalkan mereka bertiga dengan segenggam janji yang hangus di udara. Tanpa pelukan. Tanpa selamat tinggal.
Sejak mendengar itu, Ibu seakan berhenti tersenyum. Ia lebih sering duduk diam di beranda. Ia tak lagi menyapa Elara dengan “Sayang”, hanya dengan senyum pucat seperti senja yang kehilangan jingga.
Sering kali ia hanya duduk di bawah pohon di depan rumah, matanya menembus dedaunan yang tak bergerak, seolah menanti Tuhan mengembalikan sesuatu yang tak akan pulang. “Elara,” katanya suatu malam, “kalau suatu hari Ibu pergi… jangan dendam pada dunia. Dendam itu cuma api yang membakar tangan kita sendiri.”
Dan benar: tubuh Ibu perlahan menjadi seperti daun menguning—kering, diam, dan mudah roboh. Ia sering batuk darah saat malam sunyi. Tapi setiap kali Elara panik, Ibu hanya tersenyum kecil dan berkata:
“Hanya angin malam yang terlalu tajam, itu saja.” Lama-lama, tubuh Ibu tinggal tulang dan napas yang tercabik-cabik. Tapi ia masih mencoba tersenyum.
Lalu, pada suatu subuh yang begitu tenang—terlalu tenang—ia memanggil Elara, memeluknya dengan lengan yang tinggal bayang, dan berbisik seperti daun jatuh: “Maaf, Elara… Ibu nggak cukup kuat jadi rumah buatmu. Tapi kamu harus tetap berdiri, ya.”
Ia pergi. Tanpa teriakan. Tanpa guncang. Seperti malam yang habis perlahan. Dan Elara, dalam sunyi yang menggema. Bukan hanya boneka dari Ayahnya yang tak ada, kini ibunya pergi tanpa kembali lagi.
Hari pemakaman Ibu diguyur gerimis yang tidak deras, tapi cukup untuk membuat tanah menjadi lumpur. Di tengah kerumunan kecil, Elara melihat ayahnya datang… bersama wanita itu. Wanita dengan tas mahal, pakaian rapi, dan wajah tenang seperti tak ada yang salah.
Ayahnya tidak menangis. Hanya berdiri. Tidak bicara pada Elara dan nenek. Hanya menunduk—bukan karena hormat, tapi karena tak berani melihat apa yang telah ia hancurkan. Nenek Elara sempat gemetar. Elara hanya berdiri diam, menatap mereka berdua seperti menatap patung batu yang tak berhak ada di sana.
Dalam hatinya, ia menjerit: “Ibu mati karena kalian! Karena kalian, rumah ini hancur! Tuhan, jika Kau mendengar… jangan ampuni mereka sekarang. Biarkan mereka hidup cukup lama untuk tahu rasanya kehilangan yang tidak bisa ditawar.”
Tapi tak ada kata yang keluar. Karena Elara tahu: kadang, luka paling dalam tidak punya suara. Hanya tatap yang tak bisa dilupakan.
*****
Di sekolah, Elara seperti nama yang tidak disebut. Ia duduk di sudut kelas, mendengarkan guru seperti mendengarkan radio dari zaman yang lain. “Lara, kamu kenapa belakangan ini sering diam?” Wali kelasnya memanggil.
Elara tersenyum. “Saya memang selalu diam, Bu.” Tapi dalam hatinya: “Kalau aku bicara, Ibu tak akan tahan mendengarnya.”
Pulang sekolah, ia melewati jembatan kecil. Sungai di bawahnya berwarna hitam seperti ingatan yang tak pernah selesai. Ia berdiri lama, menatap air yang mengalir pelan. “Kalau aku jatuh sekarang, Tuhan… apa Kau akan menengok?” Tapi angin hanya lewat. Dan sungai tetap mengalir seperti biasa.
Suatu malam, hujan turun seperti langit ikut menangis pelan. Elara pulang dari warung, menggenggam plastik berisi roti dan obat untuk neneknya. Pintu rumah sudah terbuka sedikit, angin membuatnya berderit pelan.
Di dalam, nenek tertidur di kursi goyang, batiknya menyelimuti lutut, wajahnya damai. Elara tersenyum kecil. Ia mengecup kening nenek, lalu melangkah masuk kamar.
Lampu meja menyala. Untuk pertama kalinya, Elara tak takut dengan cahaya itu. Ia duduk, menatap pantulan wajahnya sendiri di kaca. Matanya sembap. Tapi ada sesuatu yang lain. Bukan senyum, bukan tangis. Tapi kesadaran. Bahwa ia masih hidup. Bahwa di dunia yang telah mencabik banyak hal darinya, masih ada satu hal yang tinggal: ia sendiri.
Dan, di sudut kamar itu, Elara yakin: Tuhan duduk diam. Tak jauh. Tak asing. Elara tahu, Tuhan selalu bersamanya. Ia mulai menulis lagi malam itu. Bukan untuk ibu. Bukan untuk ayah. Bukan untuk siapa pun. Tapi untuk dirinya sendiri. Untuk luka-luka yang tak minta disembuhkan, hanya ingin dikenali. Ia memeluk dirinya sendiri, pelan, seolah berkata:“Aku di sini. Aku akan baik-baik saja. Karena ada Tuhan… di sudut mataku.” Dan dari luar kamar, suara batuk nenek terdengar lirih. Masih ada yang perlu dijaga. Masih ada yang ingin Elara lindungi. Dan itu cukup. Cukup untuk tetap membuatnya hidup esok hari.