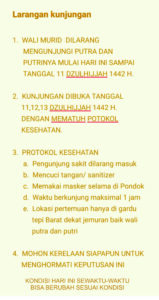Menulis telah lama menjadi inti dari tradisi keilmuan di lingkungan pondok pesantren dan madrasah. Aktivitas ini bukan sekadar rutinitas, melainkan sebuah budaya yang membentuk cara berpikir dan berkarya. Menulis menawarkan keindahan tersendiri, memfasilitasi kreativitas dalam merangkai kata, baik dalam aksara Latin maupun Arab.
Sebagai seorang santri, konsistensi dalam menulis, baik tulisan Latin maupun Arab, adalah sebuah keniscayaan. Para ulama di masa lalu menjadikan kegiatan menulis sebagai sarana utama untuk mengabadikan ilmu pengetahuan. Mereka dengan gigih mencatat setiap pelajaran yang mereka dapatkan. Semangat ini tercermin dari pesan Almuallim, guru kita, kepada salah satu santrinya, Ag. Mahfudz Birali, yang senantiasa menekankan pentingnya mendokumentasikan materi pelajaran.
Tujuan utama dari aktivitas menulis tidak hanya sebatas menjadi saksi amal kita di hari Hisab kelak, tetapi juga berperan krusial dalam menjaga kelestarian ilmu itu sendiri. Tak heran jika para ulama tak pernah berhenti menulis setiap ilmu yang mereka peroleh. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW: “Apabila engkau mendengarkan sesuatu (tentang ilmu), maka hendaklah engkau menulisnya walaupun di atas tembok” (HR. Abu Khaitsamah dalam Al-Ilmu No. 146).
Dari hadis tersebut, jelaslah bahwa menulis ilmu memiliki signifikansi yang sangat tinggi. Jika para syuhada kelak disaksikan oleh darah dan luka di sekujur tubuhnya, maka kita sebagai santri akan disaksikan oleh tinta yang tergores, keringat yang menetes, serta lembaran-lembaran kertas yang penuh coretan ilmu.
Adalah sebuah kekeliruan besar bagi siapa pun yang mengabaikan tradisi menulis atau mencatat pelajaran dengan dalih “ilmu itu di dalam hati, bukan di dalam buku.” Pemahaman semacam ini menunjukkan kekeliruan dalam memahami konteks dan esensi menulis. Mengingat ilmu itu mudah sirna jika tidak dicatat, mengabaikan tradisi menulis justru akan menjerumuskan pada kebodohan.
Oleh : Alviansyah ( KPA )